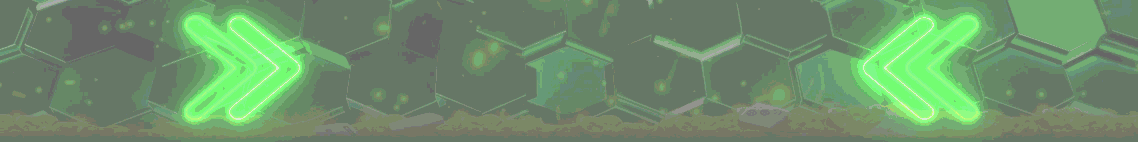Cerita Sex Dewasa – “Perhatian, semua siswa! Saya tidak mau lagi mendengar ada murid yang malas atau bolos pelajaran hanya untuk nongkrong di kantin. Kalian punya waktu khusus untuk ke kantin, dan waktu untuk belajar. Kalian sudah SMA, harus paham tanggung jawab!” tegas Bu Indah, kepala sekolah SMA-ku, dengan nada khasnya yang dingin dan tegas. Ia terkenal sebagai sosok yang jutek dan disegani, bahkan ditakuti, di seluruh sekolah.
Setiap upacara hari Senin, pidato Bu Indah selalu menyisipkan sindiran untuk siswa-siswa yang dianggapnya pemalas. Dan kali ini, lagi-lagi, aku jadi sasaran.
“Saya harus menangani siswa yang bolos, nilai ujiannya jeblok, dan tak punya semangat belajar. Saya malu, bahkan muak, melihat tingkah mereka. Tapi sebagai siswa, mereka tetap harus saya didik,” ucapnya dengan nada penuh penekanan, jelas-jelas menyinggungku.
Ini sudah kali ketiga ia menyindirku di depan umum. Kesal? Tentu saja. Tapi aku tak bisa melawan langsung, karena ia punya kuasa dan kharisma yang membuat semua orang segan. Awalnya, aku berusaha cuek dengan omongannya. Tapi lama-kelamaan, sindirannya terasa keterlaluan. Aku memutuskan, ini saatnya membalas—dan aku akan membuatnya merasakan sesuatu yang lebih pahit.
Pulang sekolah, aku berjalan sendirian. Nilai burukku jadi alasan teman-temanku menjauh, tak ada yang mau menemani. Mereka sering mengejekku, memanggilku tolol dan bego setiap hari. Di lingkungan sekolah, aku merasa seperti sampah, bahkan mungkin lebih buruk.
Di tengah perjalanan, aku mampir membeli minuman segar. Di seberang warung minuman, kulihat ada toko antik yang baru buka. Aku membayar minumanku dan langsung menyeberang, penasaran dengan toko itu.
Penjualnya seorang kakek tua yang tampak renta. Ia sedang membaca koran dengan suara terbata-bata.
“Permisi, Kek, ini toko antik, ya?” tanyaku basa-basi.
“Iya, Nak. Mau cari apa?” jawabnya dengan suara pelan.
“Cuma lihat-lihat aja, Kek,” kataku santai.
“Oh, boleh. Mau Kakek temani?” tawarnya sambil berdiri perlahan.
“Gak usah, Kek. Oh ya, ini toko baru buka, ya?” tolakku sambil memandang sekeliling, memperhatikan barang-barang antik di sana.
“Iya, Nak. Ini barang-barang Kakek dulu. Daripada nganggur, mending dijual,” jelasnya ramah.
Aku mulai menjelajahi toko. Ada mainan mobil dari kayu, cermin kaca tua, gelas keramik, sampai kaset pita Linkin Park. Tapi mataku tertuju pada sebuah buku berdebu berwarna cokelat. Di sampulnya tertulis, “Semua yang kamu tulis akan terjadi.” Aku nyaris tertawa membaca kalimat itu, menganggapnya lelucon. Tapi dalam hati, aku membayangkan sesuatu: kalau buku ini benar-benar ajaib, aku bisa membuat skenario untuk sekolahku, SMA Jaya—khususnya untuk Bu Indah, kepala sekolah yang angkuh itu.
“Kek, aku mau ini,” kataku sambil meletakkan buku di meja kasir.
“Oh, itu cuma 15 ribu, Nak,” ucap kakek itu sambil tersenyum.
“Makasih, Kek.” Aku menyerahkan uang dan berpamitan, meninggalkan toko antik itu.
Di perjalanan, aku melewati warung nasi Padang sederhana bertuliskan “Padang Harum.” Pelayannya seorang perempuan muda yang cantik dan menawan. Aku tahu dari obrolan di sekitar bahwa ia tak bisa melanjutkan kuliah karena keterbatasan ekonomi. Aku memutuskan mampir dan memesan nasi rendang dengan sambal hijau. Seorang gadis muda, sepertinya masih SMA, mendekatiku dengan seragam putih dan celana pendek.
“Mau es teh manis satu, ya,” pesanku.
Rasa penasaran membuatku membuka buku cokelat itu. Dengan ragu, aku mengambil pulpen dan menulis, “Mbak-mbak di warung nasi Padang kagum padaku dan memberi makan gratis untukku.” Aku menulis kalimat itu, tapi tak ada reaksi apa-apa. Aku hanya menunggu, agak skeptis.
Tak lama, nasi rendang dan es teh manis pesananku datang. Warung itu memang sepi, tapi yang mengejutkan, mbak pelayan tadi duduk di sebelahku.
“Makan yang banyak, ya. Kamu lagi tumbuh, jadi harus makan banyak,” katanya dengan nada semangat yang terdengar agak aneh bagiku.
“Iya, Mbak,” jawabku polos.
Apa buku ini benar-benar berhasil? Sepertinya iya.
“Kamu aku gratisin aja, ya. Tadi aku lihat kamu jalan sendirian, kasihan. Kalau laper, mampir ke sini aja, gak usah bayar,” ujar mbak itu sambil tersenyum.
Aku terkejut. Kalimat di buku itu benar-benar bekerja! Setelah selesai makan, aku mencuci tangan dan berterima kasih pada mbak pelayan. Dalam hati, aku sudah merencanakan sesuatu untuk hari esok: membalas dendam pada Bu Indah.
Keesokan harinya di sekolah, teman sebangkuku yang agak culun tapi mau menemaniku bertanya, “Eh, lu gak jajan?”
“Enggak, gua lagi gak laper,” tolakku. Waktu istirahat adalah saat yang tepat untuk melancarkan rencanaku.
Aku membuka buku cokelat itu perlahan dan menulis, “Bu Indah, Kepala Sekolah SMA Jaya, memanggilku ke ruangannya dan mengizinkanku untuk tidak mengikuti pelajaran hari ini.”
Selesai menulis, aku menutup buku. Beberapa menit kemudian, temanku tiba-tiba memanggil, “Eh, lu disuruh ke ruangan kepala sekolah!”
“Hahaha, udah gak dipanggil BK, sekarang kepala sekolah langsung!” ejeknya sambil terkekeh. Aku kesal dengan sifatnya yang manipulatif dan suka nyinyir, tapi aku diam saja. Dia tak tahu apa yang sebenarnya akan terjadi.
Aku berjalan menuju ruang kepala sekolah, dengan buku cokelat itu terselip di tas. Apa yang kutulis akan segera terbukti.
Aku mengetuk pintu ruang kepala sekolah, jantungan sedikit karena buku ajaib itu kugenggam erat. Bu Indah, dengan pesonanya yang tegas, duduk di kursi sambil menatap layar laptop. Aku menutup pintu perlahan, suasana mendadak terasa intim.
“Duduk, Yan,” perintahnya dengan suara yang dingin tapi menggoda, khas Bu Indah yang selalu punya aura berwibawa.
“Baik, Bu. Ibu panggil saya untuk apa?” tanyaku, pura-pura polos sambil mencuri pandang ke wajahnya yang cantik.
“Nilai kamu jelek. Guru BK sudah angkat tangan, makanya kamu saya panggil. Ini sudah kelewat batas, Yan. Mau tidak mau, kamu harus mengulang,” ucapnya tegas, matanya menatapku tajam, seolah menantang.
“Gak ada jalan lain, Bu?” tanyaku, sengaja memainkan nada memelas.
“Tidak ada. Sudah terlambat,” jawabnya tanpa ampun, sikapnya kaku seperti biasa.
Aku membuka buku cokelat itu, berpura-pura mencatat sesuatu. “Boleh saya tulis catatan untuk memperbaiki diri, Bu?” kataku, menyembunyikan senyum licik.
(Bu Indah merasa kegerahan meski AC menyala, dan badannya pegal-pegal.)
Bu Indah memang punya daya tarik yang sulit diabaikan. Tubuhnya yang proporsional, dengan lekuk pinggul yang menggoda dan payudara yang pas dengan tinggi badannya, membuatnya terlihat seksi. Kulitnya putih mulus, alisnya melengkung sempurna, dan wajahnya begitu memikat. Bayangan dia kepanasan justru membuatku semakin tergoda.
“Jadi bagaimana, Bu?” tanyaku lagi, sengaja memancing.
“Aduh, kenapa gerah banget, padahal AC nyala,” keluhnya, mengipasi diri dengan buku di tangannya, wajahnya mulai memerah.
“Saya gak gerah, Bu. Mungkin Ibu habis makan pedas?” godaku, sengaja melempar senyum nakal.
“Jangan sok tahu, urus nilai kamu!” bentaknya, tapi keringat mulai bermunculan di dahinya, membuatnya terlihat semakin menarik.
“Aduh, leherku pegal,” tambahnya, memijat lehernya sendiri dengan gerakan yang entah kenapa terlihat mengundang.
Aku buru-buru menulis lagi di buku. (Setiap aku memijatnya, Bu Indah merasa nyaman dan gelisah kalau aku pergi.)
Aku bangkit dari kursi, mendekatinya dengan percaya diri. “Boleh saya bantu pijat, Bu?” tawarku, tanganku sudah menyentuh lehernya dengan lembut. Anehnya, dia tidak menolak sama sekali.
“Bu, kayaknya Ibu kecapekan,” kataku, jari-jari ku mulai memijat dengan penuh perhitungan.
“Hmm, enak sekali pijatanmu, Yan,” ucapnya, suaranya mendadak lembut, hampir seperti bisikan yang menggoda.
“Kalau Ibu pegal, panggil saya aja. Saya siap bantu kapan pun,” kataku, sengaja menatap matanya dalam-dalam.
“Iya, nanti kalau pegal lagi, aku panggil kamu,” jawabnya, suaranya kini terdengar manja.
Sambil memijat lehernya, mataku tak bisa lepas dari dadanya yang penuh, terlihat menonjol di balik seragamnya. Rasa ingin menyentuhnya begitu kuat, tapi aku harus sabar. Aku menulis lagi di buku.
(Bu Indah menyuruhku tetap di sini, dan tubuhnya bebas ku sentuh dalam keadaan sadar.)
Bel masuk berbunyi, dan aku pura-pura hendak pergi. “Bu, saya harus masuk kelas. Pak Adi bakal marah kalau saya bolos pelajaran matematika,” kataku, menguji reaksinya.
“Tunggu, Yan. Gak usah masuk dulu,” ucapnya cepat, lalu mengambil telepon dan menghubungi Pak Adi. “Pak, maaf, Riyan ada keperluan dengan saya, jadi dia tidak bisa masuk kelas dulu.”
Aku tersenyum dalam hati. “Gak apa-apa, Bu?” tanyaku, pura-pura khawatir.
Bu Indah bangkit, mengunci pintu ruangannya, dan tiba-tiba suasana berubah. Ia mendekatiku, gerakannya seolah sengaja menggoda. Kami duduk di sofa, begitu dekat hingga aromanya memenuhi indraku.
“Badanku pegal banget, Yan. Beberapa hari ini banyak acara,” ceritanya, suaranya kini lembut, hampir seperti merayu.
“Boleh saya pegang bagian lain, Bu? Biar lebih rileks,” kataku, tanganku mulai meraba lengannya dengan lembut, lalu perlahan ke payudaranya. Aku menahan napas, tapi dia hanya tersenyum, seolah menikmati sentuhanku.
“Jangan teriak, Bu. Anggap ini bagian dari pijatan, ya,” kataku, mulai meremas payudaranya dengan penuh percaya diri, bahkan mencubit perlahan.
“Hmm, pertama kali aku lihat pijatan begini,” ucapnya, suaranya penuh godaan meski ada nada genit di dalamnya.
“Ini bagus untuk peredaran darah, Bu,” bohongku, menikmati setiap detik.
Aku menulis lagi di buku. (Bu Indah akan menurutku dan memanggilku ‘Beb’.)
“Tetekku sakit, Yan. Sudah, ganti pijatannya,” pintanya, tapi nadanya tetap lembut.
“Beb, ini kan bagus untuk kamu,” kataku, sengaja memanggilnya dengan panggilan baru.
“Oh, iya, Beb. Maaf, aku salah tadi,” jawabnya, tiba-tiba manja, seolah aku adalah kekasihnya.
“Beb, kalau gerah, ganti baju seksi aja di ruangan ini, kayak di film-film. Gak usah pakai hijab lagi, ya,” godaku, sengaja mendorong batas.
“Iya, Beb. Nanti aku minta suamiku beli baju seksi, bilangnya untuk dia, padahal buat aku pakai di sekolah ketemu kamu,” jawabnya, nadanya penuh kelucuan yang menggoda.
Aku melepas hijabnya perlahan, meletakkannya di meja. Rambut hitamnya yang tergerai membuatnya terlihat seperti wanita yang jauh lebih muda, penuh pesona. “Beb, aku gak suka kalau kamu nyindir aku di pidato. Kamu kan sayang sama aku, kenapa gitu?” kataku, sengaja memainkan peran.
“Maaf, Beb. Aku janji gak gitu lagi,” jawabnya, suaranya penuh penyesalan yang manis.
“Izin buka bajumu, ya, Beb,” kataku, mulai membuka kancing kemejanya. Bra putih besar terlihat, menutupi payudaranya yang menggoda. Aku meletakkan kemejanya di meja, di bawah hijabnya.
“Ih, aku malu, Beb. Tetekku kelihatan sama murid,” katanya, tangannya menutupi dadanya, tapi matanya seolah mengundang.
“Indah, mulai sekarang jangan malu. Aku pacarmu di sekolah. Kamu nurut sama aku, manja sama aku, gak peduli aku siswa. Kamu jatuh cinta sama aku, Beb,” kataku, mengelus pipinya lalu mencium bibirnya dengan penuh gairah.
“Tapi, Beb, aku kan punya suami. Susah bagi cintanya,” ucapnya, suaranya penuh keraguan yang menggoda.
“Suamimu bukan prioritas lagi. Kamu cinta banget sama aku, Beb,” balasku, menarik tangannya dan membuka branya. Payudaranya yang besar dengan puting cokelat terlihat begitu menggoda. Dia benar-benar memikat.
“Iya, Beb, sekarang kamu prioritas aku,” katanya, lalu menciumku dengan penuh gairah, lidahnya bermain-main.
Aku meremas payudaranya, menarik putingnya, dan dia hanya tertawa, menikmati setiap sentuhan. Aku mengambil ponselku, merekam momen ini. Bu Indah seolah lupa diri, menikmati ciumanku. Dari duduk, kami berpindah ke posisi berbaring di sofa, dia di atasku, menciumku berulang-ulang.
“Uhh, tetekmu mantap banget, Beb,” kataku, mencium payudaranya dengan penuh nafsu.
“Makasih, Beb. Aku senang banget,” jawabnya, suaranya penuh kepuasan.
“Indah, aku panggil kamu Indah aja kalau kita berdua, ya. Nanti kita chatting biar seru,” kataku, sengaja memperpanjang
permainan.
“Iya, Beb. Aku kasih nomorku nanti, setelah kamu puas nikmatin tubuhku,” ucapnya, nadanya penuh rayuan.
“Beb, kulum aku, dong,” pintaku, suaraku penuh perintah.
Tanpa ragu, Bu Indah berlutut, membuka celanaku, dan mulai menciumku di sana. Ia mengulum dengan penuh semangat, seolah lupa bahwa dia adalah kepala sekolah yang angkuh. Aku bersandar, bermain game di ponsel sambil sesekali mengelus kepalanya. Untungnya, tak ada yang mengetuk pintu.
Setelah 30 menit, aku mencapai klimaks, dan cairanku membanjiri mulutnya. “Telan, Beb. Itu kesukaanmu,” kataku.
“Iya, Beb. Aku suka banget,” jawabnya, menelan semuanya dengan lihai, seolah sudah terbiasa.
“Beb, nanti bantu aku kerjain tugas, ya. Kalau perlu, kamu yang selesaikan semua,” kataku, menatapnya penuh kendali.
“Iya, Beb. Tugasmu aku kerjain,” jawabnya, duduk di sampingku dengan manja.
“Sekarang buka celanamu, Beb,” pintaku, menciumnya lagi.
Ia berdiri, melepas celana panjangnya, lalu celana dalam putihnya. Area intimnya yang lebat terlihat, tapi aku tahu ini akan jadi bagian dari kesenangan. “Beb, cukur itu nanti, ya,” kataku, melepas bajuku sendiri.
“Iya, Beb. Aku cukur setiap kali tumbuh,” jawabnya tanpa rasa malu, memamerkan tubuh telanjangnya.
“Sekarang pakai celana dalammu di wajah, Beb,” perintahku. Ia mengambil celana dalamnya dan memakainya seperti topeng, membuatku tergelak. Aku memotretnya, kepala sekolah yang kini begitu memalukan.
“Sekarang merangkak dan bersuara seperti anjing, Indah,” kataku. Ia langsung melakukannya dengan sempurna.
“Guk guk guk! Wlaf!” suaranya, penuh ketaatan.
“Anjing pintar, Indah,” pujiku, mengelus kepalanya.
“Guk guk!” jawabnya, terlihat bahagia.
“Aku ke kantin bentar, Beb. Kamu tunggu di sini,” kataku, mengambil dua lembar uang seratus ribu dari dompetnya yang penuh.
“Guk!” Ia mengangguk.
Aku membuka kunci pintu, memastikan tak ada orang di luar, lalu mengunci lagi ruangan itu. Di kantin, aku membeli dua potong ayam goreng krispi dan es teh manis.
“Kamu nanti dimarahin Bu Indah lagi kalau ketahuan,” kata penjual es teh, tersenyum.
“Ini buat Bu Indah, kok,” bohongku, menahan tawa karena dia tak tahu kepala sekolah itu kini jadi “anjing” peliharaanku.
Kembali ke ruangan, aku hampir saja bertabrakan dengan Pak Adi. Jantungan, tapi aku tetap tenang.
“Kamu ke kantin, ya?” tanyanya ketus.
“Iya, Pak. Ini disuruh Bu Indah. Saya mau ke ruangannya sekarang,” jawabku, berusaha santai.
“Jangan bohong!” bentaknya.
“Bener, Pak,” kataku, berjalan ke pintu ruangan dan pura-pura membukanya. Untungnya, Pak Adi percaya.
Di dalam, Bu Indah menungguku dengan manis, tangannya memeluk payudaranya, lidahnya sedikit menjulur seperti anjing setia. “Tadi ketemu Pak Adi, untung dia percaya,” kataku, tersenyum.
“Guk guk guk!” jawabnya, menggonggong lucu.
“Buka celana dalam di wajahmu, Beb, dan makan ini,” perintahku, melemparkan ayam goreng ke lantai.
Ia memakan ayam itu dengan lahap, seperti anjing sungguhan, sementara aku merekamnya sambil menyeruput es teh. Kepala sekolah yang angkuh kini jadi hiburanku.
Aku menulis lagi di buku. (Setiap hari, Bu Indah akan mengabariku untuk datang ke ruangannya.
Permainan ini baru saja dimulai, dan aku tahu, dia akan selalu berada di bawah kendaliku.
Bu Indah akan menjadi pelayanku selamanya. Jabatan kepala sekolah hanyalah topeng luarnya.
Selesai makan dengan penuh nafsu, mulutnya belepotan sisa daging ayam. Tulang-tulangnya pun dilahap habis, tak peduli sekeras apa pun. Aku mengambil tisu dari meja kerjanya, mengelap wajahnya yang kini memandangku dengan manja, seperti anak kecil yang menanti pujian.
“Kembali jadi manusia biasa, Beb. Duduk di sofa,” perintahku lembut tapi tegas.
“Iya, Beb,” jawabnya, menurut dengan tatapan kosong yang menggoda. Ia duduk di sofa, tubuhnya seolah menanti sentuhanku.
“Indah, sekarang tiduran, lebarkan pahamu,” kataku, suaraku penuh kendali.
Tanpa ragu, Bu Indah merebahkan diri, kedua tangannya membuka pahanya, memamerkan area intimnya yang lebat. Aku melepas celanaku, mendekat, dan perlahan mencoba masuk ke dalamnya.
“Hmm, sakit, Beb,” erangnya, suaranya lembut tapi penuh daya tarik.
“Kamu harus menikmati ini, Indah,” kataku, menatap matanya yang mulai berkaca-kaca.
“Iya, Beb,” jawabnya patuh. Aku mendorong lebih dalam, dan dia menahan desahan, takut suaranya terdengar ke luar.
Kami bercinta dengan penuh gairah. Tanganku meremas payudaranya yang montok, lalu menjilati lehernya dengan rakus. Ia mendesah pelan, tubuhnya merespons setiap sentuhanku. Aku tak memberi ampun, menikmati setiap detik kekuasaanku atasnya.
“Enak?” tanyaku, sengaja memancing.
“Enak, Beb… enak banget,” desahnya, suaranya penuh kepuasan yang liar.
“KAMU LACUR TOLOL! NYINDIR AKU DI UPACARA, DIKIRA AKU GAK SAKIT HATI? INI BALASANNYA!” bentakku, mendorong lebih keras sambil menampar payudaranya hingga memerah.
“Iya… aku lacurmu, Beb… ahh, enak… maafin Indah… Indah salah nyindir kamu…” desahnya, suaranya campur aduk antara kenikmatan dan penyesalan.
“Kamu harus bertanggung jawab,” kataku, menampar pipinya dengan lembut tapi tegas.
“Iya, Indah bertanggung jawab… ahhh,” jawabnya, semakin tenggelam dalam kenikmatan.
“Lebih enak mana dibandingkan suamimu, Indah?” Aku menarik diri sejenak, lalu masuk lagi dengan kasar.
“KAMU… AHH… LEBIH ENAK… DARI SUAMIKU… AHH… ENAK BANGET, BEB… DARI SIAPA PUN!” jeritnya, suaranya liar, hampir tak
terkendali.
Aku tak peduli apakah ada yang mendengar. Yang penting, dia milikku sepenuhnya.
“Indah, mulai sekarang ini cuma untukku. Tolak suamimu kalau dia mengajak bercinta,” perintahku.
“IYA… AHH… INI HANYA UNTUKMU, BEB!” jawabnya, tubuhnya bergetar.
Menikmati tubuhnya yang menggoda terasa begitu memuaskan. Aku membalikkan posisi, kini dia di atasku, menggoyangkan tubuhnya dengan liar. Payudaranya naik-turun dengan indah, dan aku tersenyum jahat. Kepala sekolah yang angkuh kini kutaklukkan dengan mudah.
“Enak… ahh… enak banget, Beb…” desahnya, semakin tak bisa mengendalikan diri.
Aku mengambil buku ajaib itu dan menulis. (Setiap kujentikkan jari, dia sadar kembali, tapi saat kupanggil ‘Beb,’ dia terhipnotis lagi.)
Saat dia asyik menikmati diriku, aku menjentikkan jari. Matanya membelalak.
“APA INI?!” teriaknya, mencoba melepaskan diri, tapi aku tetap menggerakkan tubuhku dengan penuh kendali. Ia berusaha menahan desahan, wajahnya memerah karena malu.
“Enak, kan, Bu?” godaku, tersenyum licik.
“Lepaskan! Aku gak mau bercinta denganmu!” bentaknya, mendorongku dengan lemah.
Tapi aku memegang lengannya erat. Ia menggeleng, menahan tangis. “Hentikan, Yan! Aku akan laporkan kamu ke polisi!” ancamnya.
“Aku gak peduli, Bu. Yang penting aku sudah menikmati tubuh Ibu,” kataku santai, terus mendorong hingga mencapai klimaks lagi.
“Ahh… kamu jahat…” desahnya lemas, tubuhnya terkapar.
Ia berusaha meraih ponselnya, tapi aku menariknya dan kembali masuk ke dalamnya, kali ini dengan posisi doggy style berdiri. “Spermaku sudah di dalam rahim Ibu. Nikmati saja, Bu. Ibu pasti senang,” kataku, penuh percaya diri.
“Lepaskan! Aku gak mau hamil dari anak sepertimu! Kamu akan dipenjara karena memperkosaku!” bentaknya, berusaha meraih ponselnya lagi.
Aku membiarkannya mengambil ponsel. Ia menelpon suaminya, tapi sebelum ia bicara, aku berkata, “Beb, kenapa sih gak mau?”
Sekilas, ia terhipnotis lagi. “Ada apa, Sayang? Kamu ngos-ngosan?” tanya suaminya di telepon.
“Enggak, Sayang. Tadi kepencet doang,” jawab Bu Indah, mendekatiku dan memegangku lagi, menyandarkan tubuhnya ke dinding sambil memasukkan diriku ke dalamnya.
“Serius gak apa-apa?” tanya suaminya, khawatir.
“Gak apa-apa. Tadi cari dokumen, panik sedikit karena gak ketemu,” bohongnya, menahan desahan sambil menikmati diriku.
“Oke, Sayang. Aku lanjut kerja dulu, ya,” kata suaminya polos, lalu menutup telepon.
Begitu telepon ditutup, Bu Indah melepaskan desahan penuh nikmat. Aku menarik tubuhnya, menciumnya dengan penuh gairah. Ia membalas ciumanku dengan liar. Tapi aku menjentikkan jari lagi.
“Kamu kenapa cium aku?!” bentaknya, mendorongku dengan marah.
“Ibu yang membalas ciumanku, kok marah?” kataku, pura-pura heran.
“Kurang ajar!” Ia melempar benda di dekatnya, tapi aku menangkapnya. Ia menangis, tak bisa berkata apa-apa.
Ia berlari ke pakaiannya, buru-buru memakai bra dan celana dalam. Aku hanya memandang, menggenggam diriku yang masih tegang. “Dasar mesum! Aku pastikan kamu dikeluarkan dari sekolah ini!” ancamnya, mengenakan celananya dan merapikan kemejanya. Ia mengambil hijabnya, memakainya dengan cepat hingga hanya wajahnya yang terlihat.
“Ibu mau keluarkan saya?” tanyaku, sengaja menantang.
“Tentu saja! Kamu melecehkanku! Kamu akan masuk penjara dan menyesal!” bentaknya, membuka kunci pintu dengan tergesa.
“Beb, kamu lupa siapa dirimu, ya?” kataku lembut.
Ia langsung mengunci pintu lagi, berjalan ke arahku, lalu berlutut, mencium kakiku. “Maaf, Beb. Aku lupa aku harus nurut sama kamu,” ucapnya, suaranya penuh penyesalan yang manja.
“Aku capek kalau kamu pura-pura begini,” kataku, mendorong tubuhnya dengan kakiku.
“Maaf, Beb. Aku gak akan gitu lagi. Aku nurut sama kamu,” janjinya, matanya memohon.
“Tujuanmu apa, Indah?” tanyaku, mengangkat tubuhnya hingga berdiri.
“Melayani kamu, Beb. Perintahmu adalah kewajibanku. Aku mau sama kamu terus, bukan sama suamiku,” jawabnya, penuh ketaatan.
“Bagus. Itulah dirimu sekarang. Melayaniku, mengabdi padaku. Kau kepala sekolah, tapi kamu patuh pada muridmu ini,” kataku, mendekatinya, meremas dadanya yang sudah tertutup pakaian dengan keras.
“Iya, Beb. Aku patuh padamu,” jawabnya, tersenyum manis.
Aku duduk di sofa. Bu Indah berjongkok, membuka celanaku, dan kembali mengulumku dengan penuh semangat. Sambil menikmati, aku mengambil ponselnya, memesan pakaian seksi dan ketat lewat akun belanja onlinenya. Aku tak peduli berapa yang kuhabiskan—lima ratus ribu lebih untuk mainan erotis dan pakaian menggoda. Semua dari rekeningnya, dan aku tahu, dia akan membiarkannya demi aku.
Keesokan harinya saat pelajaran Bahasa Indonesia..
“Eh, Yan, lu gak takut? Bu Widya lagi nerangin kalimat aktif sama pasif, lho,” bisik Anton, temen sebangkuku, sambil melirikku yang asyik main game di ponsel.
“Jadi, kalian sudah paham, kan, bedanya kalimat aktif dan pasif?” tanya Bu Widya dengan wajah ramah, suaranya lembut saat menatap ke arah kelas.
Tapi keramahannya cuma sekejap. Begitu matanya nyangkut ke aku, wajahnya langsung berubah. “Yan, dari tadi Ibu lihat kamu main hp terus!” bentaknya, nada ramahnya lenyap seketika.
Aku kaget, buru-buru matiin ponsel. Anton cuma geleng-geleng kepala, seolah bilang ‘dasar nekat’. Aku nggak berani nengok ke Bu Widya. Guru senior ini terkenal killer, bahkan Pak Ardi yang galak aja kalah dibandingkan dia. Senyum manisnya cuma topeng—di baliknya, dia kejam dan pelit banget soal nilai.
Aku udah sering kena hukuman darinya: berjemur di lapangan, nyikat toilet, sampai jalan jongkok keliling lapangan. Yang bikin kesel, dia selalu bandingin aku sama anaknya yang katanya disiplin dan sempurna. Angkuh banget, meremehkan murid-muridnya seolah kami nggak ada apa-apanya.
“Maaf, Bu,” cuma itu yang keluar dari mulutku, suaraku pelan.
“Maaf apaan?! Kalau nggak niat belajar, keluar aja! Main game sana, gak usah sekolah! Anak Ibu nggak pernah kayak kamu, dia selalu fokus!” bentaknya lagi, kata-katanya menusuk. Teman-teman sekelas ada yang nyengir, bisik-bisik, tapi sebagian cuek aja.
“Bu, saya janji gak main game lagi,” rayuku, berharap dia luluh.
“Gak ada janji-janji! Keluar sekarang, bersihin toilet! Kalau toiletnya bersih, baru kamu boleh masuk kelas Ibu lagi!” perintahnya ketus. Tawa kecil dari temen-temen makin bikin aku panas.
Aku keluar kelas dengan muka merah, tapi pas di depan papan tulis, Bu Widya tiba-tiba nyambar ponselku. “Bu, kenapa diambil?” tanyaku, kaget.
“Ponsel ini Ibu sita seminggu. Kamu harus dididik!” katanya, meletakkan ponselku di mejanya tanpa ragu.
Dengan perasaan campur aduk malu, kesel, marah—aku melangkah ke toilet pria. Aku ambil pel dan ember, lalu mulai isi air. Keran kecil banget, bikin aku harus nunggu lama. Dalam hati, aku udah niat: Bu Widya bakal jadi target buku ajaibku.
Aku buka buku cokelat itu dan menulis: *Bu Widya akan mendatangiku, meminta maaf karena marah, dan membantu membersihkan toilet.*
Bu Widya, meski usianya 35, punya pesona yang susah dilupain. Tinggi, tubuhnya proporsional, pinggulnya menggoda, dan payudaranya bulat meski nggak terlalu besar. Wajahnya cantik, khas perempuan Sunda, dengan alis tebal dan bibir merona yang bikin aku kadang ngebayang hal-hal nakal dengannya.
Tak lama, Bu Widya beneran datang ke toilet. Untung toilet pria lagi sepi, jadi nggak ada saksi. “Ibu ngapain ke sini?” tanyaku, pura-pura kaget.
“Ibu mau bicara sama kamu, Yan,” jawabnya, suaranya lebih lembut dari biasanya.
“Biar nggak dicurigain, masuk ke bilik toilet aja, Bu,” usulku, sengaja bikin situasi jadi lebih intim.
“Iya, bener juga,” katanya, mengangguk.
Kami masuk ke bilik toilet sempit, cuma 2×2 meter, dengan kloset jongkok dan ember penuh air. Air keran tiba-tiba mengalir kencang, seolah mendukung rencanaku. Berhadapan di ruang sesempit ini, suasananya terasa panas.
“Ibu mau ngomong apa? Oh ya, kelas nggak curiga, kan? Jarang-jarang Ibu ninggalin kelas tiba-tiba,” tanyaku, pura-pura polos.
“Ibu bohong, bilang ke anak-anak mau ke ruang guru buat ngobrol sama kepala sekolah,” jelasnya, suaranya agak malu-malu.
“Bu Widya bohong, dong?” godaku, tertawa kecil biar suasana cair.
“Ibu mau minta maaf, Yan. Hukuman kayak gini pasti capek, apalagi bukan sekali-dua kali kamu kena. Ibu merasa bersalah. Maafin Ibu, ya?” katanya, wajahnya memelas. Aku nggak pernah lihat Bu Widya sekuyu ini sebelumnya.
“Aku maafin, Bu,” jawabku santai, meski dalam hati aku girang.
“Ibu bantu bersihin, ya,” tawarnya, langsung mengambil pel, mencelupkannya ke ember, lalu mulai ngepel dengan serius.
Aku membuka buku lagi, menulis: *Saat aku panggil ‘Beb,’ Bu Widya akan jadi budakku sepenuhnya. Tak peduli seburuk apa aku, aku adalah tuannya.
Aku nulis sambil mencuri pandang ke pinggulnya yang hampir menyentuh wajahku saat dia jongkok ngepel. “Bu, ini gak apa-apa, kan?” tanyaku, pura-pura khawatir.
“Gak apa-apa, Yan. Kamu lihat aja Ibu bersihin,” jawabnya, fokus ngepel dengan detail.
“Beb, kalau capek, bilang, ya. Biar aku gantian,” kataku, sengaja pakai panggilan ‘Beb.’
Dia langsung berdiri dari posisi jongkok, menatapku dengan mata kosong, lalu tersenyum manis. “Beb, aku bersihin ini sendiri, ya. Kamu gak usah khawatir,” ucapnya, suaranya lembut dan patuh.
Aku tersenyum dalam hati. Bu Widya, guru killer yang angkuh, kini kutaklukkan dalam sekejap.
“Beb, kayaknya kalau pakai seragam guru gitu panas, ya. Mendingan nggak pakai apa-apa aja,” kataku dengan nada bercanda, pikiran nakal mengambil alih. Bu Widya, tanpa ragu, mulai membuka seragamnya. Sapu pel yang tadi dipegangnya disandarkan ke dinding. Ia melepas hijabnya dengan gerakan lembut, lalu menggantungkannya di hanger. Kedua tangannya perlahan membuka kancing kemeja, memperlihatkan bra hitam bermotif bunga. Dengan penuh percaya diri, ia melepaskan pakaiannya satu per satu, tanpa sedikit pun rasa malu. Aku mendekat, tanganku meraba payudaranya, dan ia tidak menolak.
“Payudaramu cukup oke untuk tinggi badanmu,” ujarku, setengah menggoda.
“Makasih, Beb,” jawabnya sambil tersenyum kecil. Ia lalu membuka celananya, menumpuknya bersama hijab di gantungan.
“Beb, nanti sering-sering olahraga yang bisa bikin payudaramu lebih besar, ya. Masa cuma begini doang,” kataku sambil meremasnya pelan, masih dengan nada bercanda.
“Iya, Beb, aku akan coba apa saja biar payudaraku lebih besar,” balas Bu Widya dengan antusias.
Ia kemudian melepas bra-nya, memperlihatkan payudaranya yang terlihat begitu alami. Aku tak bisa menahan diri dan langsung mendekat, menjilati putingnya sementara ia berusaha melepas celana dalamnya dengan sedikit kesulitan. Kini, ia benar-benar telanjang. Bu Widya kembali memegang sapu pel, namun kali ini aku meremas payudaranya lagi dan sesekali menampar pantatnya yang mulus. Ia hanya tersenyum, tidak menolak atau mengeluh.
“Bu, jangan marah-marah lagi di kelas, ya,” kataku setengah memerintah.
“Iya, Beb, aku nggak akan marah lagi. Kalau kamu berisik di kelas, itu hakmu, dan aku akan menghargainya. Aku akan mengajar tanpa peduli muridku nakal atau nggak,” ujar Bu Widya dengan nada pasrah, seolah ia rela membiarkan kenakalan di kelas terjadi.
Tiba-tiba aku teringat, Bu Widya punya suami, Pak Imas, guru PPKn di sekolahku. Dia orangnya pendiam, pelajarannya cenderung membosankan. “Bu, telepon Pak Imas, dong. Ajak aku makan malam bareng,” pintaku.
“Baik, Beb, aku telepon sekarang,” jawabnya. Ia mengambil ponsel dari saku celananya dan mulai menghubungi Pak Imas. Teleponnya berdering beberapa kali, sepertinya Pak Imas sedang mengajar.
Sambil menunggu, aku membuka celanaku, mengelus kemaluanku, dan mendekatkannya ke area intim Bu Widya. Dengan hati-hati, aku memasukkan kemaluanku ke dalam vaginanya. Ia mendesah pelan, mencoba menahan suara.
“Tahan, Bu, nanti ketahuan orang lain,” bisikku sambil memegang pinggulnya dan mendorong lebih dalam. Aku tahu ia merasakan sedikit rasa sakit, tapi ekspresinya menunjukkan ia menikmatinya.
Akhirnya, di panggilan kelima, Pak Imas menjawab. “Kenapa, Bu? Tadi aku lagi ngajar, keluar kelas gara-gara ibu telepon,” katanya dengan nada khawatir.
“Hmm, nggak apa-apa, Pak. Aku cuma mau bilang, aku mau ajak salah satu muridku makan malam. Dia jago di pelajaran, jadi kayak bentuk apresiasi,” ujar Bu Widya, padahal aku sendiri malas belajar.
“Tumben banget ajak murid makan malam. Siapa, sih?” tanya Pak Imas, suaranya penuh curiga.
“Riyan, Pak. Dia bener-bener berubah, sekarang rajin belajar,” kata Bu Widya sambil memandangku, tangannya masih memegang ponsel.
“Suara apa itu? Riyan? Murid pemalas itu? Males banget lihat mukanya,” balas Pak Imas dengan nada ketus.
“Apa, sih, Pak? Riyan lagi berusaha jadi lebih baik. Kamu sebagai guru malah nggak dukung, marah-marah mulu,” Bu Widya membalas dengan nada kesal.
Saat itu, aku mengubah posisi, memindahkan kemaluanku ke anusnya. Bu Widya buru-buru menutup mulutnya, menahan rasa sakit yang tiba-tiba.
“Bu, mana mungkin Riyan tiba-tiba pinter. Kemarin aja dia dipanggil kepala sekolah,” sergah Pak Imas.
“Dia udah berubah, Pak! Aku capek sama kamu. Pokoknya, Riyan ikut makan malam nanti di restoran!” Bu Widya mematikan telepon dengan kesal.
“Beb, kamu berani banget, ya, sama suamimu,” kataku sambil mengubah posisi agar kami berhadapan.
“Ahhh… enak, Beb… Suamiku kalau nggak suka, ya nggak suka sama sekali,” desah Bu Widya, kini ia mulai menikmati setiap gerakan.
“Oh, gitu? Males banget punya suami kayak gitu,” ujarku sambil terus bergerak.
“AHHHH, BENER, BEB! AKU MALES PUNYA SUAMI KAYA DIA! AHHHH, ENAK BANGET… KEMALUANMU BIKIN KETAGIHAN… TOLONG TERUSIN, AHHHH!” Bu Widya mendesah keras, matanya terpejam, menikmati setiap detik.
Lima belas menit lalu, ia masih menyuruhku keluar dari ruangan ini. Kini, ia benar-benar menyerah pada hasrat. “Kalau suamimu tahu kita begini, apa kabar?” tanyaku sambil mencium payudaranya.
“BODO AMAT! AKU LEBIH SUKA BEGINI SAMA KAMU DARIPADA SAMA SUAMIKU! AHHHH!” Bu Widya berteriak, tubuhnya bergetar saat aku mencapai klimaks di dalam anusnya.
Aku mengambil buku ajaib itu. Setiap kali aku menjentikkan jari, ia akan sadar. Tapi saat aku memanggilnya ‘Beb’, ia akan kembali terhipnotis.
Aku sebenarnya malas menulis target berikutnya di buku itu, tapi aku akan menjalaninya demi menaklukkan sekolah ini.
Tiba-tiba, terdengar suara beberapa siswa di luar, sedang mengobrol tentang tubuh seksi Bu Indah, guru lain di sekolah. Mereka berfantasi ingin berhubungan intim dengannya. Aku tersenyum dalam hati. Dua wanita di sekolah ini sudah kutaklukkan.
Aku menjentikkan jari. Bu Widya tersentak, kaget. Dengan cepat, aku memasukkan kemaluanku kembali ke vaginanya dan menutup mulutnya. “Kalau Ibu berisik, bisa ketahuan,” bisikku.
“Hmmm…” Ia menahan suara, wajahnya panik.
Di luar, para siswa masih mengobrol. “Bayangin lo ngewe sama Bu Indah pas dia pidato di upacara, kayak di film bokep Jepang!” kata salah satu.
“Gue sih pengen ngewe dia sambil jalan keliling sekolah. Payudaranya yang besar itu gue remas, anjir, montok banget!” sahut yang lain.
Mereka terus mengobrol mesum, tak sadar di ruangan sebelah sedang terjadi sesuatu. “Tolong… aku nggak kuat lagi, Beb… Ibu janji bakal jaga rahasia ini,” mohon Bu Widya, suaranya bercampur tangis dan desahan.
“Enak, kan, Bu?” tanyaku sambil terus bergerak, menargetkan titik sensitifnya.
“Enggak… ahhh… tolong, Riyan… ampun…” pintanya lagi, suaranya melemah.
Suara anak-anak di luar mulai menjauh. “Beb, kamu harus suka ini,” kataku. Seketika, ia kembali terhipnotis.
“AHHHH, IYA, BEB! AKU SUKA BANGET! INI JAUH LEBIH ENAK DARIPADA SUAMIKU! AHHHH, ENAK BANGET!” Bu Widya mendesah liar, tubuhnya menyerah sepenuhnya.
Aku menjilati lehernya yang basah oleh keringat. Ruangan yang sempit membuat suasana semakin panas. “Nanti tolong reservasi di restoran Dapur Solo yang mewah itu, ya. Jangan lupa minta ruangan privat,” pintaku.
“BAIK, BEB! AHHHH!” jawabnya dengan penuh semangat.
Aku mencapai klimaks lagi, kali ini di vaginanya. Ia tersenyum, menciumku dengan penuh gairah. Aku menampar pahanya dengan kemaluanku, lalu kami berciuman panas. “Beb, jongkok di WC jongkok, pose mesum,” kataku sambil mengambil ponselku.
“Iya, Beb,” jawabnya patuh. Ia jongkok, kedua tangan di belakang kepala, memperlihatkan payudara dan vaginanya dengan jelas. Aku memotretnya, dan ia tampak menikmati peran sebagai model mesumku.
Aku berdiri di depannya, memasukkan kemaluanku ke mulutnya. Aku mendorong hingga ia tersedak, sambil menyiram tubuhnya dengan air dari keran. Ia basah, lengket, dan berbau sperma. “Slurpp…” Ia menikmati setiap detik.
Kali ini, aku tidak mengeluarkan sperma, melainkan air kencing. Bu Widya menelannya, wajahnya penuh kepuasan. “Beb, berak, dong. Aku videoin,” kataku sambil tertawa kecil.
“Iya, Beb,” jawabnya. Ia berusaha mengeluarkan kotorannya, dan aku merekamnya dengan ponselku, tertawa jahat. Kotorannya keluar dari anusnya, menjijikkan tapi entah kenapa aku menikmatinya. Bu Widya tampak senang, seolah bangga dengan apa yang dilakukannya. Setelah selesai, kuperintahkan ia membersihkan sisa kotoran di pantatnya.
Bu Widya kembali memakai seragamnya, begitu juga aku. Kami merapikan penampilan, seolah tak ada yang terjadi.
Waktu sudah malam tepat menunjukkan waktu makan malam yang sudah ku minta ke Bu Widya
“Bu ini kenapa diruangan privat gini deh.” Ucap Pak Imas.
Aku, Bu Widya, dan Pak Imas bertiga duduk di ruangan VIP Restoran, kita disajikan banyak masakan.
“Ini biar kita terkesan dekat aja pak.” Jawab Bu Widya.
Aku memakai kemeja biru dengan celana putih. Pak Imas dengan kaos kerah hitam dimasukkin dan jeans yang ikat pinggangnya terlihat kuno. Bu Widya memakai kemeja putih dengan terlihat BH hitamnya, tidak lupa celana ketat yang dia dulu pakai pas masih kurus. Pak Imas awalnya menolak namun ia tidak bisa melawan kemauan istrinya.
“Kamu yang rekomendasikan ini? Dapur Solo mahal jangan kuras harta istri saya.” Ketus Pak Imas
“Engga Pak, ibu yang mau. Riyan hanya ikut saja.” Bohong Bu Widya.
“Yasudah mari kita makan.” Pak Imas mengambil gudeg dan sayuran.
Bu Widya mengambil ayam, dendeng sapi, dan telor. Aku mengambil ayam saja.
“Hmm enakk.” ucap Bu Widya
“Ibu banyak amat porsi makannya.” Pak Imas heran dengan istrinya yang biasanya ga suka makan sekarang justru makan banyak.
“Bapak tu ngeluh terus ya!! cape aku dengernya. Aku mau berisi badannya pak biar ga kurus kurus amat.” Tegas Bu Widya
“Iya maaf bu.” Pak Imas tak bisa melawan
Aku dalam hati tertawa melihat suami istri ribut karena pengaruh buku ajaibku.
Kakiku di paha Bu Widya lalu aku mendorong jemariku ke memeknya yang tertutup celana dalam. Bu Widya kaget namun dia mencob tidak terjadi apa apa. Dia ingin rasanya mendesah.
“Pak gimana enak?” Tanyaku
“Ga usah sok basa basi, saya malas ketemu kamu sebenernya.” Ucap Pak Imas sambil makan rendangnya.
“Apaan si pak? kamu kalo aku undang orang hargain dong jangan gini, aku ga suka bapak sikap kaya gini.” Ketus Bu Widya menatap tajam suaminya
“Tapi bu, dia tu pemalas. Kamu sendiri sering cerita kalau benci ketemu dia.” Kata suami Bu Widya yang mengambil gelasnya untuk minum
“Riyan sudah berubah, kamu ga percayaan ya.” Malas Bu Widya menanggapi suaminya.
“Ya udah pak aku minta maaf banget, aku keluar deh dari sini. Aku bisa makan diluar.” Aku keluar dari bangkuku lalu mencuci tanganku di wastafel privat.
“Kan pak, aku jadi ga enak sama Riyan. Riyan tu mau belajar pak, kenapa bapak selalu benci gitu si. Ibu benci sama bapak. Ga usah mesra mesraan lagi, aku mau kita juga pisah ranjang.” Kata Bu Widya
Wow ternyata Bu Widya seberani itu ya.
“Ibu ko jadi ngomong gini.” Heran Pak Imas
“Maaf ya pak bu saya pergi.” Aku mendekati pintu lalu Bu Widya menarik tanganku
“Ibu mohon lanjutkan makannya, ibu minta maaf banget buat gaduh.” Ngemis Bu Widya depan suaminya
“Bu, Apa yang buat ibu berubah ke Riyan? ibu mohon mohon ke dia.” Tanya Pak Imas
“Apaan si pak, dia tamu anjing, dia tamu aku tolol, aku ajak dia biar kita makan bareng.” Ucap Bu Widya
“Bu jangan ngomong kasar ga enak dengernya.” Aku mencoba menenangkan Bu Widya
“Ini pertama kali ibu ngomong ke bapak gini.” Kaget Pak Imas.
( Pak Imas tidak bisa bergerak ketika aku melecehkan istrinya )
“Beb kamu jangan marah marah lagi ya.” Kataku sambil mencium bibirnya.
Bu Widya membalas dengan french kiss.
“KALIAN BERDUA NGAPAIN, BU BERHENTI.” Marah Pak Imas
“Beb suami aku berisik bacot bener.” Kata Bu Widya
“Iya beb.” Aku cium lagi sambil meremas pantatnya.
“Kenapa aku ga bisa gerak, Bu hentikan tolong.” Kata Pak Imas
“Beb telanjang dong, aku mau nyoba kamu.” Kataku sambil meraba payudaranya
“Ehh kamu Riyan, saya telpon polisi biar dipenjarakan.” Ancam Pak Imas yang percuma saja karena tidak bisa keluar dari bangkunya dan tak bisa bergerak.
Bu Widya membuka kancingnya, Pak Imas teriak meminta udahan. Bu Widya menghiraukan dan menunjukkan BH serta celana dalamnya. Bu Widya menari di depanku.
“Bu kenapa tegaa buuu.” Tangis Pak Imas melihat istrinya berselingkuh dengan muridnya sendiri.
( Pak Imas membuka celananya ketika Bu Widya telanjang bulat dan mulai mengocok penisnnya ketika istrinya ngewe dengan Riyan)
“Beb kamu seksi banget tapi harus digedein lagi ya.” Aku meraba perutnya
“Baik beb, makanya aku sekarang makan banyak dan mau member gym.” Ucap Bu Widya
“Eh kamu ngapain suruh suruh istri saya.” Marah Pak Imas
“Apa yang dipinta Riyan itu tanggung jawab aku, kamu ga usah ikut campur.” Tegas Bu Widya.
“Pak Imas liat istrii bapak layani saya ya.” kataku sambil membukakan BH dan Celana Dalamnya.
Pak Imas secara ga sadar membukakan celannya, Pak Imas menunjukkan kontolnya yang kecil. Aku tertawa melihatnya
“Liat beb kecil tu.” Ejek aku
“Hahaha benar beb, makanya aku udah ga mau sama dia.” Kata Bu Widya
Pak Imas menggelengkan kepala, bingung kenapa ia buka celana. Kontolnya yang ngaceng tetap terlihat kecil bagi Bu Widya.
Tanganku masuk menusuk memeknya Bu Widya. Aku colmek Bu Widya di depan suaminya. Disisi lain aku menjilati payudaranya dengan nikmat.
“AHHHH BEBBBBBBB ENAKK OUGHHH.” Bu Widya mendesah.
“Buuu hentikannn jangannnn.” Tangis Pak Imas semakin keras.
Ruangan ini kedap suara jadi desahan Bu Widya tidak akan terdengar. Bu Widya memegang meja untuk menahan tubuhnya.
“Kocok aja pak kontolnya hahaha.” Suruhku
“Kamu jahat Riyan, kamu lecehin istri saya.” Kata Pak Imas sambil menangis
“Kamu lebih pilih aku atau suami kamu Beb?” Tanyaku yang semakin keras menggesek memeknya.
“Ahhhhh kamuuuu kamuuuuu Riyannnn. Kamu lebih aku sayang daripada suami aku. Riyannn Bebbbb Oughhhh tolongg bantu akuuu biar makin sayang ahhhhh hmmmm samaa kamu.” Kata Bu Widya
“Ibu ko bisa ngomong gitu.” Kata Pak Imas mengerutkan dahinya
“Kamu tu kontolnya kecil, kamu sibuk, kamu overthinking, kamu selalu negatif ke orang yang kamu benci. Aku udah ga sayang lagi sama kamu. Aku sayangnya Riyan.” Bu Widya melihat Suaminya dengan tatapan sinis
Memek Bu Widya ingin memuncratkan cairan. Ku bawa tubuh Bu Widya di depan tubuh suaminya. Ku gendong Bu Widya dengan posisi kepala di wajahku dan memeknya di depan suaminya. Ku gesek lagi hingga cairan keluar ke muka Pak Imas.
“Enak sayang beb.” kata Bu Widya
Tak hanya cairan biasa, Bu Widya juga kencing di depan muka Pak Imas. Bau pesing istrinya jadi saksi kalau Bu Widya sudah tak tahu malu lagi.
Ku turunkan Bu Widya lalu Ku masukkan kontolku ke memek Bu Widya. Dia semangat sekali menerimanya. Kedua tangan Bu Widya berpangku ke suaminya. Kita melakukan Seks dengan gaya doggy style.
“Hmm tusukan kontol kamu enak banget Beb.” Ucap Bu Widya
“Kamu rebut istri saya.” Kata Pak Imas
“Aku yang mau pak, aku yang bersedia melayani Riyan bukan kemauan Riyan.” Jelas Bu Widya yang teteknya gondal gandil untung saja aku remas keras teteknya.
Kontol Pak Imas mulai dikocok oleh tangannya sendiri. Bu Widya ketawa.
“Tolol tua bangka, tau gitu ga usah aku nikah ama kamu. Ngocokin istrinya yang selingkuh. Kontol kamu tu kecil goblok.” Ejek Bu Widya
“Bu Widya siap ga kalau hidup sama aku?” Tanyaku sambil mencubit pentilnya
“AHHHHHHH AKUUU SIAAAAP BEB, AKU BAKAL CERAI DENGAN SUAMI AKU, AKU MAU TINGGAL SAMA KAMU BEB. HMMMM OUGHHHHHH.” Kata Bu Widya
“Gamauuu bu.” Kata Pak Imas terbata bata
“Ah elah aku tu udah ga ada kepikiran kamu lagi di hidupku. Lupakan aku Pak.” Jelas Bu Widya
Aku menjetikkan jari, Bu Widya langsung sadar dan kaget melihat suaminya mengocok dirinya.
“PAKK TOLONGGGGG PAKKKKK TOLONGGG AHHHHH.” Bu Widya memegang tangan Pak Imas
“Rasakan ini Bu.” Aku menusuk kontol ke memek Bu Widya lebih dalam.
“AHHHHH HMMMM TOLONGG PAKKKK SAKITTTTTTT PAKKK.” Teriak Bu Widya
“Bapak ga bisa bergerak.” Ucap Pak Imas
“Pak kok ngocokin istri sendiri si, dah mana kaya enak banget.” kataku yang mulai menampar pantat Bu Widya
“Pakkkk, BAPAKKKK JAHATTTT GAAAAA BANTUUUUU IBUU AHHHHHH AHHHHHH.” Sperma keluar di memeknya Bu Widya.
“Beb kamu puas ya?” Tanyaku yang melihat Bu Widya terkujur memeluk Pak Imas.
Kontolku dilepas namun dia melepas pelukan Pak Imas. Bu Widya datang kepadaku dan menciumku.
“Najis aku meluk dia, udah ga aku anggap suami lagi dia, aku mau pisah sama dia beb.” Dia memegang kepalaku lalu menjilati leherku.
“Ibu kenapa tiba tiba berubah gini lagi?” Heran Pak Imas
“Bapak denger sendiri kan, sekarang Bu Widya milik saya. Jangan ganggu lagi.” Kataku
Aku duduk di kursi memangku Bu Widya yang mencium tubuhku. Pak Imas tidak bisa berbuat apa – apa. Aku mengambil kerupuk kulit dan ku bagikan ke Bu Widya.
“Bu balik yu bu.” Ucap Pak Imas
“Sana balik sendiri, aku mau mesra sama Riyan dulu. Kamu tadi ga bantuin aku kan malah ngocokin tolol. Kamu biarin istrinya ngewe sama orang lain yauda berarti kita udah selesai, minggu depan akan aku urusi surat cerainya. Kamu tinggalkan aku.” Jelas Bu Widya yang membuang muka dari Pak Imas.
Kontol yang masih tegang ini ku masukan ke memeknya. Dengan santainya aku ngewr lagi meskipun Pak Imas sudah tak berdaya melihat isrtinya direbut murid yang paling dua benci.
Dua hari setelah aku “mengambil alih” Bu Widya dari suaminya, pelajaran Bahasa Indonesia terasa lebih cepat berlalu. Bu Widya beralasan ingin istirahat, tapi kenyataannya, ia menghabiskan waktu di toilet pria, mengulum kemaluanku dan menggesek vaginanya hingga klimaks. Tentu saja, itu bersamaku.
Bu Widya dan Pak Imas masih tinggal serumah, tapi ia berencana mengajukan perceraian besok. Pak Imas, seperti biasa, hanya menurut pada keinginan istrinya tanpa banyak protes.
Di sisi lain, aku mendapat uang seratus ribu per hari dari Bu Indah, kepala sekolah. Ia juga sering membelikanku makanan dari restoran mewah saat aku di rumah. Tak hanya itu, ia kerap mengirimkan foto-foto payudaranya atau pose mesum lainnya lewat chat. Kami sering mengobrol, terutama saat jam istirahat. Ia suka memanggilku ke ruang kepala sekolah, untungnya tak ada yang curiga. Di sana, Bu Indah selalu mencium kemaluanku dan meminta spermaku untuk ditelan. Hingga kini, suaminya tidak tahu bahwa istrinya berselingkuh denganku.
Usai istirahat, aku kembali ke kelas sambil membawa minuman. Di ponselku, ada pesan
dari Bu Indah: foto payudaranya sambil ia menulis dokumen di meja. Aku langsung menyukainya.
Yuda: Beb, gedein dong tetekmu biar lebih nikmat diremes.
Bu Indah: Iya, Beb, aku udah daftar gym kok buat bikin tetekku lebih besar. Aku kalo di rumah kangen banget diremes sama kamu, tau nggak.
Yuda: Hehe, nikmat dong remesanku.
Bu Indah: Iyaaa, Beb, muach!
Aku tersenyum, lalu duduk di bangku. Ketua kelas mengumumkan bahwa jam pelajaran kali ini kosong. Tanpa buang waktu, aku membuka game di ponselku.
Saat asyik bermain, tiba-tiba Rara, bendahara kelas yang galak, menghampiriku. Rara dikenal ketus dan selalu ranking satu di kelas. Wajahnya sudah memasang ekspresi kesal.
“Cepet bayar, lu udah nunggak kas satu bulan!” bentaknya.
“Sabar, Rara, gua lagi main game,” jawabku santai, fokus ke layar ponsel.
“Alasan! Bilang aja lu miskin, nggak mampu bayar!” serunya, menatapku tajam.
“Nanti gua bayar abis game ini, tenang,” kataku, masih asyik dengan permainanku.
“EH, TOLOL, BAYAR SEKARANG! LU MISKIN, JANGAN SOK GAYA! LU TAU, GUA BISA BELI LU MURAH!” Rara menggebrak mejaku, membuat seisi kelas terdiam.
“Apaan, sih? Gua bilang bakal bayar, kok bawa-bawa miskin segala!” balasku, mulai kesal.
“Emang lu miskin! Bokap lu kan nggak kerja, ibu lu cuma jualan gorengan!” Rara tertawa, dan beberapa teman kelas ikut terkekeh.
Aku benar-benar geram. Kata-katanya menyakitkan, tapi aku menahan diri. Rara memasang wajah angkuh, seolah menikmati momen itu. Ketua kelas, yang seharusnya menengahi, malah tertidur di belakang. Memang, hampir semua teman sekelas tak menyukaiku, mungkin karena aku dianggap paling miskin. Tapi mereka tak tahu, aku punya “senjata” yang bisa mengubah keadaan.
“Eh, tolol, kalo nggak mau bayar, mending nggak usah sekolah!” Rara mendorong tubuhku dengan kasar.
Aku mematikan game, mengambil dompet, lalu berdiri menghadapnya. Kuberikan dua ratus ribu untuk bayar kas tiga bulan ke depan. “Nih, kan?” kataku datar.
“Wah, banyak duit juga lu. Ngepet, ya? Jadi babi?” ejek Rara lagi, sinis.
“Udah bayar, kan?” ujarku, berusaha tetap tenang.
“Songong banget, lu! Udah nunggak berapa minggu, masih gaya. Miskin tolol, ortu lu juga tolol!” serunya, kali ini mendorong kepalaku.
“Ejek gua ya ejek gua aja, nggak usah bawa-bawa keluarga!” balasku, suaraku meninggi.
“Emang lu miskin, anjing! Hahaha!” Rara tertawa puas, lalu kembali ke bangkunya sambil memamerkan kemesraan dengan pacarnya, Rio, cowok basket yang gaya tapi pemalas. Rio bahkan lebih malas dariku, sering absen saat tugas kelompok tapi selalu ngotot bilang dia berperan penting.
(Aku menjentikkan jari. Seketika, vagina Rara terasa sangat gatal, hanya bisa reda jika digaruk orang lain. Dan dia hanya bisa ke toilet untuk meredakannya.)
“Sayang, nanti pulang mau makan di tempat yang kemarin aku kasih tau, nggak?” tanya Rio, mesra.
“Boleh, Sayang,” jawab Rara sambil tersenyum manis.
Tiba-tiba, Rara menjauh sedikit dari Rio. Pahanya dirapatkan, lalu ia menggesek-gesekkannya pelan. Aku pura-pura main game, tapi mataku memperhatikan setiap gerakannya.
“Kenapa, Sayang?” tanya Rio, khawatir.
“Gatel banget… di sini,” bisik Rara, suaranya pelan tapi panik.
(Saat aku mendekatinya, rasa gatal itu meningkat drastis.)
Rio berusaha melindungi Rara dengan tubuhnya, tapi aku tetap bisa melihat. Rara mulai menggesek vaginanya lebih cepat, tangannya masuk ke dalam celana, mencoba meredakan gatal. Wajahnya penuh ketegangan, seolah tak bisa menahan rasa itu. Rio tampak semakin cemas, tapi anehnya, teman-teman sekelas tak menyadari apa yang terjadi.
“Aku nggak tahan, Rio…” keluh Rara dengan suara parau, hampir menangis.
Aku mendekati Rio dan menyerahkan uang dua puluh ribu kepadanya.
“Ngapain lo ke sini, tolol?” tanya Rio dengan nada sinis. Di sampingnya, Rara tampak gelisah, tangannya bergerak-gerak dengan canggung.
“Gue kayaknya punya utang sama lo,” kataku pelan.
“Utang apa?” Rio melirik ke arah pacarnya, alisnya terangkat.
“Waktu itu lo taruhan, kan? Kalau gue berhasil masukin bola basket, gue boleh pergi. Tapi kalau nggak, gue kasih lo duit,” jelasku, mencoba mengingatkannya.
“Oh, tumben lo ingat. Apa gara-gara cewek gue yang ngingetin, ya? Hahaha, tolol!” Rio tertawa lepas, nada ejekannya terdengar jelas.
Tiba-tiba, Rara berdiri dengan gerakan canggung, tangannya masih bergerak di area yang membuat semua mata tertuju padanya. Aku pura-pura nggak tahu apa-apa, tapi teman-teman di kelas mulai berbisik.
“Rara, kenapa lo berdiri gitu sambil… pegang-pegang gitu?” tanya salah satu temen ceweknya, suaranya penuh kebingungan.
“NGGAK TAHAN! GATAL BANGET!” Rara hampir berteriak, wajahnya memerah.
“Ran, kendaliin dong tangan lo!”
“Rara, berhenti!”
“Lo udah gede, masa gitu doang nggak bisa tahan?”
“Ran, tahan dong!”
“Lepasin tangan lo, Ra!”
Kata-kata itu bergema di kelas, bercampur dengan suara cekikikan dan bisik-bisik kaget.
“BACOT KALIAN! GUE GATAL BANGET!” Rara buru-buru keluar kelas, tangannya masih bergerak canggung. Dia menunduk, air matanya mulai jatuh. Rio buru-buru mengejar, tapi langsung didorong oleh Rara.
“Aku beliin obat, ya?” tawar Rio, suaranya penuh khawatir.
“Nggak usah! Aku mau ke toilet!” Rara menjawab dengan nada terbata-bata, lalu berlari pergi.
Aku tersenyum dalam hati. Rencanaku berjalan mulus.
Tak lama kemudian, aku izin ke ketua kelas, bilang kalau aku dipanggil kepala sekolah.
“Lo kok sering banget dipanggil bimbingan, Yan? Semoga nggak kenapa-kenapa, deh,” kata ketua kelas sambil melirik ponselku. Aku cuma nyengir. Sebelumnya, aku sudah minta Bu Indah untuk berpura-pura memanggilku.
Aku keluar kelas, sengaja memutar lewat kantor kepala sekolah sebelum menuju toilet pria. Dari kejauhan, aku mendengar suara rintihan pelan. Aku yakin itu Rara.
Toilet pria sepi, cuma ada aku. Aku mengetuk pintu bilik tempat Rara berada. Dia terdengar kaget, suaranya gemetar.
“Siapa?! Ssshh… gatal banget, sih!” suaranya lirih, tapi penuh kepanikan.
“Ra, ini gue, Riyan. Lo ngapain di toilet pria?” tanyaku, pura-pura bingung.
“Hah?! Ini toilet pria?!” Rara kaget, suaranya nyaris melengking.
Pintu bilik terbuka. Rara berdiri di depanku, rok celananya basah, mungkin karena gatal yang nggak tertahankan. Wajahnya memerah, campuran malu dan kesal.
“Apa sih lo liat-liat? Mesum!” katanya dengan nada ketus.
“Rok lo basah banget, Ra,” kataku, mencoba tetap tenang.
“Urusan gue, anjing! Mesum! Tolol!” Rara menghardik, tapi suaranya sedikit gemetar.
Aku menarik tangannya perlahan dan masuk kembali ke bilik. Mulutnya aku tutup dengan tangan, menghentikan teriakannya yang mulai keluar.
“Gue cuma mau bantu, Ra. Tapi kalau lo teriak, gue kasih tahu semua lo garuk-garuk di toilet pria,” ancamku pelan.
Rara diam, matanya melebar. “Oke, gue percaya,” katanya akhirnya, suaranya kecil.
“Dengerin, ini dari pengalaman nenek gue. Kalau gatal gitu, harus digaruk sama tangan orang lain. Percaya aja, jangan mikir aneh-aneh,” kataku, mencoba meyakinkan.
“Mau mesum, ya, lo?!” bisik Rara, nadanya curiga.
Tiba-tiba, terdengar suara langkah masuk ke toilet. Aku mendekat ke Rara. “Kalau lo teriak sekarang, malah dicurigain. Lo kan nggak teriak dari tadi,” kataku pelan.
Rara menatapku tajam. “Anjing, lo mau mainin gue, ya?”
“Enggak, Ra. Ini beneran, gatalnya bakal hilang,” kataku, berusaha meyakinkan.
“Kalau nggak ilang, gue teriak. Bodo amat lo digebukin atau dikeluarin dari sekolah,” ketus Rara.
“Gue tutup mata biar nggak lihat, oke?” tawarku.
“Ya udah, boleh,” jawabnya pelan.
Rara membuka roknya perlahan dan menggantungkannya di pintu. Aku menutup mata, sesuai janji. Tanganku dipegangnya, lalu diarahkan ke area yang gatal. Aku merasakan kulitnya yang halus, bersih, dan… sepertinya dia rajin merawat diri.
“Gue coba, ya,” kataku, mulai menggesek perlahan.
“Eh, gatalnya mulai reda…” Rara terdengar kaget, suaranya bergetar.
“Percaya, kan?” kataku sambil terus menggesek, kali ini sedikit lebih cepat.
“Hmm… iya, gue percaya,” jawabnya, suaranya mulai berdesah pelan.
Aku mempercepat gerakan, tetap dengan mata tertutup. Rara diam, tapi aku bisa mendengar napasnya yang semakin berat.
“Hmm… enak… ohh…” Rara berusaha menahan desahannya.
Gesekan tanganku semakin terasa, jari-jariku bergerak dengan lebih lincah. Rara memegang pundakku, menarikku lebih dekat ke lehernya.
“Mau udahan, Ra?” tanyaku.
“Ohh… jangan dulu, Yan! Tolong… enak…” Rara seperti lupa diri, suaranya penuh kenikmatan.
“Udah nggak gatal, kan?” kataku, tetap menggesek.
“Iya… tapi… lo bikin gue… naik, Yan! Jangan berhenti… ahh!” desahnya semakin keras.
“Boleh buka mata nggak?” tanyaku.
“Boleh… gapapa… ahh…” jawabnya, suaranya terputus-putus.
Aku membuka mata. Wajah Rara penuh kenikmatan, matanya terpejam, mulutnya sedikit terbuka mengeluarkan desahan. Keringat membasahi wajahnya, seragamnya basah memperlihatkan sedikit warna bra birunya yang kontras dengan kulit putihnya.
“Lo nggak mau berhenti dulu?” tanyaku lagi.
“Enggak… biarin… gatalnya ilang… ahh…” Rara memejamkan mata lebih erat.
Tak lama kemudian, tubuh Rara menegang, dan cairan memuncrat dari tubuhnya ke arah toilet jongkok.
“Masih gatal?” tanyaku, menarik tanganku.
“Enggak, Yan. Makasih, ya… tolong jangan bilang siapa-siapa,” pintanya dengan nada memelas.
“Aman, Ra,” jawabku santai.
Dia buru-buru memakai roknya kembali. Aku mencuci tangan, lalu mengeringkannya di seragamku. Saat dia merapikan pakaiannya, aku menulis sesuatu di buku catatanku.
(Seperti biasa, siapa pun yang kupanggil “beb” akan mutlak mengikuti keinginanku.)
“Gue balik ke kelas, ya,” kata Rara, berjalan keluar.
“Lo nggak mau coba sama gue, beb?” kataku sambil tersenyum kecil.
Rara berbalik, mendekatiku dengan tatapan berbeda. “Maaf, beb, aku lupa ngikutin mau kamu,” katanya lembut, tangannya memegang pundakku.
“Cium aku,” pintaku.
Dia mendekat, tapi ciumannya kaku, seperti dia belum terbiasa. Rara memang montok, kulitnya putih, tapi sepertinya dia terlalu fokus dengan ekskul paskibranya untuk memikirkan hal-hal seperti ini.
“Lo kulum kontol gue,” kataku, menciumnya lagi.
Rara turun, membuka celanaku dengan gerakan canggung. Kontolku sudah di depan wajahnya. Aku menampar pipinya pelan dengan itu, lalu memasukkannya ke mulutnya. Dia memegangnya dengan malu-malu, gerakannya kaku.
“Pertama kali, ya, Ra?” tanyaku sambil mengelus jilbabnya.
“Iya, beb… kurang enak, ya? Maaf banget,” jawabnya dengan suara lirih, mulutnya penuh.
Aku nggak mengeluarkan sperma, tapi air kencing. Jilbabnya basah, bau pesing. Anehnya, Rara tersenyum setelah menelannya.
“Makasih, beb, enak,” katanya, wajahnya polos.
“Cuci muka lo, Ra,” suruhku.
Dia mengangguk, mengambil air, dan membersihkan wajahnya. Jilbabnya yang basah sepertinya nggak mengganggunya.
“Nanti di kelas, lo buka celana lo dan pose mesum di depan semua orang. Lo bakal seneng banget telanjang, ketimbang pake baju,” kataku sambil meremas payudaranya.
“Iya, beb, telanjang lebih enak daripada pake seragam,” jawabnya dengan antusias.
Kami keluar dari toilet. “Aku ke kantin dulu, ya,” kataku, mencium bibirnya yang masih sedikit bau.
“Iya, beb,” jawab Rara, lalu berjalan pergi.
Di kantin, aku beli dua potong dada ayam goreng, bayar, dan kembali ke kelas. Sesampainya di sana, pintu kelas tertutup, jendela juga. Aku mendengar suara ribut dari dalam, campuran ketakutan dan teriakan.
“Ra, lo kenapa?!” teriak Rio, suaranya panik.
“Ra, lo stress, ya, kok gini?!” tanya temen lain.
Aku membuka pintu, dan pemandangan di depanku bikin kaget sekaligus puas. Rara berdiri di depan kelas, cuma pakai jilbab, telanjang bulat. Kedua tangannya di belakang kepala, pahanya terbuka lebar.
“TELANJANG ENAK BANGET, KALIAN HARUS COBA!” teriak Rara, lidahnya menjulur nakal.
“Tutup pintu, tolol!” bentak Rio padaku.
Aku menutup pintu, pura-pura nggak tahu apa-apa. Tapi di dalam hati, aku menikmati kekacauan ini.
“TELANJANG ENAK BANGET, TAU! KALIAN HARUS COBA!” teriak Rara, lidahnya menjulur dengan ekspresi liar, seperti kehilangan kendali.
“Rara seksi banget, anjir,” bisik salah satu temen cowokku, suaranya pelan agar nggak kedengeran Rio. Sebenarnya, nggak perlu munafik tubuh Rara memang menarik perhatian, montok dan proporsional.
Aku melangkah mendekati Rara, lalu memasukkan kontolku ke memeknya. Seketika, suasana kelas memanas. Satu per satu, temen-temen mulai membuka baju mereka, seolah terbawa suasana. Melihat Rara telanjang bulat begitu, hasrat mereka seperti meledak, nggak peduli lagi soal keperjakaan atau keperawanan. Tapi Rio? Dia cuma berdiri di tempat, matanya merah, tangannya gemetar. Bukannya ikut, dia malah mulai mengocok kontolnya sambil menatap Rara dan aku.
“Ra, udah, pakai seragam lagi, dong,” kata Rio dengan suara lembut, hampir memohon.
“Lo nggak usah ngatur-ngatur gue lagi, Rio. Maaf, gue udah muak sama lo. Kita putus,” balas Rara ketus, tanpa ragu.
Seluruh kelas terdiam, pandangan tertuju pada Rio. Dia menggelengkan kepala, wajahnya penuh kekecewaan, hampir menangis. Aku nggak peduli. Aku melempar potongan dada ayam goreng yang tadi kubeli ke lantai di depan Rara.
“Makan, Ra. Makan kayak anjing,” kataku, setengah bercanda.
Rara tersenyum kecil, lalu merangkak, memakan ayam itu tanpa protes. Teman cewek di sebelahku kaget, matanya membelalak.
“Eh, kok lo nurut sama si Riyan?” tanyanya, suaranya penuh keheranan.
Aku nggak menjawab. Dengan gerakan cepat, aku membuka celanaku dan memasukkan kontolku ke memek Rara lagi. Rio langsung melangkah mendekat, wajahnya memerah karena marah, tinjunya terkepal.
“ANJING, LO NGAPAIN!” teriak Rio, siap memukulku. Tapi tiba-tiba dia berhenti, tangannya gemetar, lalu membuka celananya sendiri. Dia mulai mengocok kontolnya dengan panik.
“ANJING, APAAN INI?! KENAPA TANGAN GUE?!” teriaknya, suaranya penuh kebingungan dan keputusasaan.
“Ih, ngocok pas ngeliat pacarnya, tolol,” ejekku, sengaja menambah panas suasana.
Aku meremas payudara Rara, mencubit pentilnya perlahan. Rara mendesah, “Guk… guk…” Wajahnya penuh kenikmatan, seperti nggak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya.
“Panas banget, anjir!” tiba-tiba salah satu temen cewekku berseru. Dia perlahan melepas jilbabnya, lalu membuka kancing seragamnya tanpa ragu. Ketua kelas, yang biasanya kalem, tiba-tiba mendekat dan menjilati payudaranya.
“Eh, lo mesum, ngapain?!” protes temen cewek lain, mencoba menarik ketua kelas.
“Jangan munafik, deh! Cowo-cowo juga tadi ngeliatin Rara, kan? Kalian juga pada pengen, ngaku!” balas ketua kelas dengan nada tegas.
Cewek yang tadi protes tiba-tiba diam, lalu malah berkata, “Ya udah, pakai aku, Ketua.”
Satu per satu, cewek-cewek di kelas mulai membuka jilbab dan seragam mereka. Cowo-cowo nggak kalah, membuka celana dan memamerkan kontol mereka. Suasana kelas berubah jadi liar, penuh hasrat. Satu per satu, mereka mulai bercampur, memasukkan kontol ke memek masing-masing, seperti lupa diri. Rara masih merangkak, mulutnya penuh ayam goreng, berantakan. Aku menariknya mendekat ke wajah Rio, yang cuma bisa menangis dalam diam, matanya penuh keputusasaan.